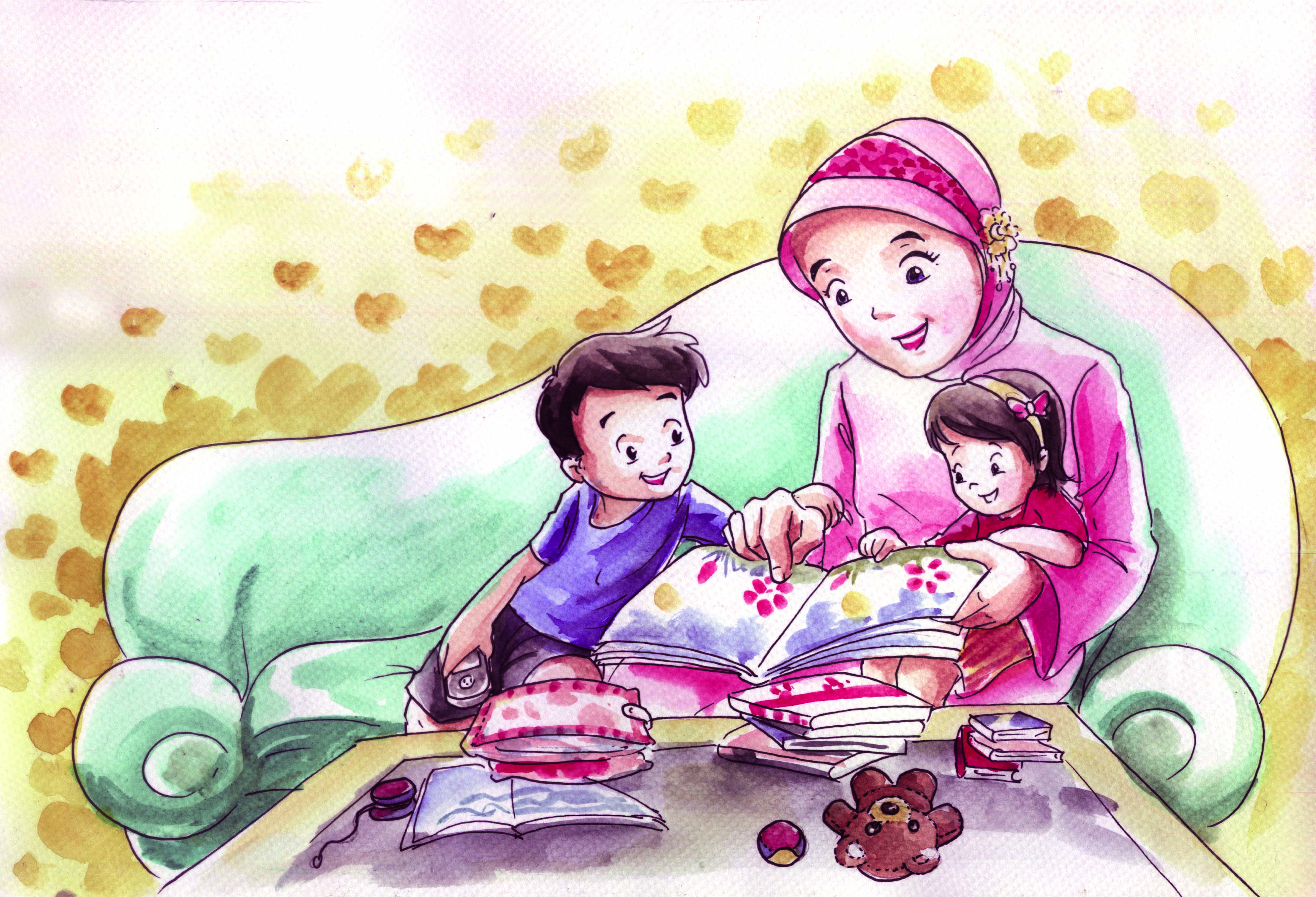
Anak dan Budi Pekerti
“bocah saiki ancene ora koyok bocah mbiyen” (anak sekarang memang tidak seperti anak dulu). Fenomena tersebut seringkali diucapkan bahkan dijadikan sebuah penelitian, namun menurut pengamatan pribadi penulis, keadaan juga tidak banyak berubah. Penulis masih melihat ada anak kecil tidak mau mencium tangan orang yang lebih tua, anak kecil yang mengucapkan “kepo” ketika ditanya kenapa atau ada apa, dan bahkan anak kecil yang berani memfitnah gurunya untuk dilaporkan kepada orang tua. Belum lagi beberapa obrolan wali murid yang menginginkan anaknya seperti si A, yang walaupun tidak pintar namun mempunyai karakter yang baik. Sehingga penulis merasa ada pergeseran karakter pada masa modern saat ini.
Ketika masih kecil, orang tua penulis sangat memperhatikan tentang akhlak atau budi pekerti terhadap sesama manusia, bahkan terhadap hewan sekalipun. Tentunya sebuah zaman memiliki karakternya masing-masing, artinya budaya setiap zaman dengan zaman lainnya bisa berbeda. Contohnya pada masa lalu, budaya ketika suasana lebaran, orang-orang berbondong-bondong untuk berkeliling saling bermaaf-maafan. Namun penulis melihat pada saat ini itu semua sudah bergeser dengan fenomena broadcast selamat lebaran tanpa harus bersusah payah untuk berkeliling. Budaya berkeliling bermaaf-maafan setidaknya akan memunculkan pribadi yang berkarakter dalam diri anak. Ketika anak-anak diajak berkeliling meminta maaf, mereka akan melihat bagaimana orang tua mereka mencium tangan orang yang lebih tua atau dicium tangannya oleh yang lebih muda. Secara tidak langsung itu adalah habituasi bagi anak, agar mereka lambat laun memahami bahwa yang muda harus menghormati yang tua dan yang tua harus menyayangi yang muda. Belum lagi bagaimana komunikasi orang tua mereka dengan orang lain, etika yang mereka gunakan ketika berkomunikasi dengan yang lebih tua atau dengan yang lebih muda, bahkan komunikasi mereka dengan orang yang tidak mempunya etika.
Problematika tersebut mengingatkan apa yang disebutkan oleh al-Ghazali, lisan al-hal afshohu min lisan al-maqal. Pernyataan al-Ghazali mengindikasikan bahwa proses dalam habituasi terhadap anak akan lebih dipahami dan ditiru daripada hanya sekedar memberikan teori atau narasi semata. Singkatnya bahwa seorang guru harus bisa digugu dan ditiru. Ketika anak diajarkan untuk menghormati orang lain, maka pendidik harus membuat habituasinya. Begitu pula ketika seorang pendidik menginginkan anak memiliki empati yang tinggi atau bisa menjaga mulutnya, maka proses keteladanan yang berbentuk budaya merupakan kunci utama. Ibaratnya ketika ada orang yang ingin mahir atau fasih berbahasa inggris, maka dia akan cepat berhasil ketika berada dalam situasi atau budaya yang serba bebahasa inggris, meskipun orang tersebut tidak banyak menguasai teori. Mungkin sudah saatnya guru untuk menghayati kembali slogan “ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani” (di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberikan daya kekuatan).
Seperti yang dikatakan dalam salah satu Hadis Nabi yang menyatakan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, atau dalam istilah filsafat dikatakan tabula rasa. Pada dasarnya, perkembangan anak semuanya tergantung bagaimana dia mendapat keteladanan dari lingkungannya.
Penulis :
Editor :
Sumber :











